Robohnya Surau Kami Akibat Doyan Beragama
Beragama saja tidak
cukup malah berbahaya. Seperti halnya makan, mengonsumsi agama secara
berlebihan bisa menyebabkan kantuk dan pusing-pusin. Pada kasus ekstrim, gelisah dan insomia. Jikalau mengalami
gejala-gejala demikian, segeralah menemui Allah – langsung tanpa perantara!
Beragama adalah jalan
menuju Allah. Jalan bukan tujuan, jalan hanya mengantarkan. Apabila terlalu
suka dengan keindahan, kemulusan, jalan, kamu bakal terjerumus ke dalam kemursyikan
karena kamu sebenarnya menyembah jalan. Pentingnya membedakan jalan dan tujuan terdengar
jelas dalam kata kata sang Buddha kepada murid-muridnya, “Jikalau bertemu Buddha
dalam perjalanan, bunuh saja dia!"
Agama yang benar pasti
mengijinkan 'vandalisme'. Bukan mengotori dinding kota atau menginjak-injak
tanaman yang susah-payah ditanam dinas tata kota. Apalagi mengotori ruang
media sosial dengan berita sampah atau status menghasut penuh kekejian. Vandalisme adalah ketegasan membuang setiap percabangan pemikiran yang mengaku-ngaku agamawi namun
pada dasarnya politicking alias politik busuk dalam bungkus agama. Sebelum
Allah sendiri yang ‘memangkas’ kamu, tebas dia seketika!
Jangan main-main dengan
hal ini. Tetapi, ketahuilah, banyak orang yang bermain-main di wilayah ini.
Apalagi kalau kamu golongan beragama unyu-unyu, yaitu bersikap naif dan menelan
setiap ajaran tanpa saringan, kamu menjadi wayang-wayang kecil yang
dijungkirbalikkan dalang seenaknya. Kamu menurut semata kesalehanmu, dan itu berbahaya
bagi keselamatan jiwanya di akhirat!
Saya ingat sebuah buku
yang kubaca di masa SMA, buah karya A.A. Navis, berjudul “Robohnya Surau Kami”.
Sesungguhnya ini judul cerita pendek dalam kumpulan cerita pendek. Walaupun
tidak persis pararel dengan perbincangan ini, ia layak dibicarakan secara
serius.
Cerpen “Robohnya Surau Kami” mengisahkan seorang kakek yang mewakafkan hidupnya sebagai penjaga surau (Garin). Suatu hari, ia ditemukan mati mengenaskan. Ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur.
Sepeninggalan beliau, surau yang tadinya sejuk dan damai buat sembahyang berubah suram, tak terurus dan lapuk. Anak-anak bermain tanpa peduli dengan kesakralannya sedangkan bilik serta lantai kayu surau diambil masyarakat untuk kayu bakar. Surau terhempas, surut ke dalam gelombang acuh tak acuh.
Awalnya kata kata seorang Ajo Sidi yang menceritakan kisah Haji Saleh kepada kakek penjaga surau tadi. Sebagai orang beragama, Haji Saleh sungguh patut dipuji. Ia taat menjalankan setiap perintah agama tanpa kecuali. Hidupnya dihabiskan dengan cermat demi menyembah Allah siang dan malam. Sungguh seorang yang sangat dikehendaki Tuhan, pahalanya berkarung-karung dan sudah pasti masuk surga.
Apa disangka, ia malah dimasukkan ke neraka, surga hanya impian!
Tentu saja timbul ketidakpuasaan di orang-orang yang sedang antrean masuk surga. Makin tidak puas setibanya di neraka, Haji Saleh bertemu teman-teman sangat saleh seperti dirinya bahkan ada yang bergelar syech. Mereka merasa diperlakukan tidak adil! Haji Saleh memimpin aksi, ia berdiri paling depan dan menjadi juru bicara kaum sesalehan.
Untuk pertama kalinya, surga diguncang aksi protes, demonstrasi massal oleh mereka yang merasa telah berbuat banyak buat Allah, bukan hanya memuji bahkan membela kesucianNya semasa hidup mereka.
Cerpen “Robohnya Surau Kami” mengisahkan seorang kakek yang mewakafkan hidupnya sebagai penjaga surau (Garin). Suatu hari, ia ditemukan mati mengenaskan. Ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur.
Sepeninggalan beliau, surau yang tadinya sejuk dan damai buat sembahyang berubah suram, tak terurus dan lapuk. Anak-anak bermain tanpa peduli dengan kesakralannya sedangkan bilik serta lantai kayu surau diambil masyarakat untuk kayu bakar. Surau terhempas, surut ke dalam gelombang acuh tak acuh.
Awalnya kata kata seorang Ajo Sidi yang menceritakan kisah Haji Saleh kepada kakek penjaga surau tadi. Sebagai orang beragama, Haji Saleh sungguh patut dipuji. Ia taat menjalankan setiap perintah agama tanpa kecuali. Hidupnya dihabiskan dengan cermat demi menyembah Allah siang dan malam. Sungguh seorang yang sangat dikehendaki Tuhan, pahalanya berkarung-karung dan sudah pasti masuk surga.
Apa disangka, ia malah dimasukkan ke neraka, surga hanya impian!
Tentu saja timbul ketidakpuasaan di orang-orang yang sedang antrean masuk surga. Makin tidak puas setibanya di neraka, Haji Saleh bertemu teman-teman sangat saleh seperti dirinya bahkan ada yang bergelar syech. Mereka merasa diperlakukan tidak adil! Haji Saleh memimpin aksi, ia berdiri paling depan dan menjadi juru bicara kaum sesalehan.
Untuk pertama kalinya, surga diguncang aksi protes, demonstrasi massal oleh mereka yang merasa telah berbuat banyak buat Allah, bukan hanya memuji bahkan membela kesucianNya semasa hidup mereka.
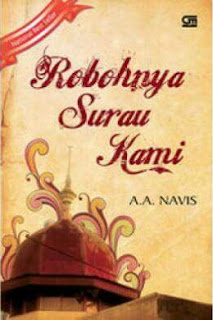 |
Tadinya ia berharap kata kata cinta dari Allah. Tak disangka-sangka, malah membuat ciut dan kejut. Kesalehan para demonstran justru dicela sebagai sikap egois. Mereka rajin menyembahNya namun abai dengan kesejahteraan orang-orang di sekeliling mereka. Mereka berasal dari negeri sekaya Indonesia dan membiarkan kekayaan bangsa diangkut orang orang asing. Ini tidak bisa dimaafkan!
Kisah Haji Saleh sebagaimana diceritakan Ajo Sidi, sangat mengganggu pikiran kakek penjaga surau. Dia sendiri hidup sangat beragama sampai-sampai rela tidak beristri dan beranak. Kepalanya bagai dihantam palu godam. Ia sampai di penghujung asa. Selembar nyawanya digadaikan ke dalam kematian prematur.
A.A. Navis sebenarnya sedang memotret kesalehan religius yang naif. Pengamatan dia sangat relevan di segala jaman karena egoisme beragama yang ia gambarkan terjadi terus-menerus. Di jaman kita, sebagian orang menyebutnya dengan istilah doyan agama.
Kisah Haji Saleh sebagaimana diceritakan Ajo Sidi, sangat mengganggu pikiran kakek penjaga surau. Dia sendiri hidup sangat beragama sampai-sampai rela tidak beristri dan beranak. Kepalanya bagai dihantam palu godam. Ia sampai di penghujung asa. Selembar nyawanya digadaikan ke dalam kematian prematur.
A.A. Navis sebenarnya sedang memotret kesalehan religius yang naif. Pengamatan dia sangat relevan di segala jaman karena egoisme beragama yang ia gambarkan terjadi terus-menerus. Di jaman kita, sebagian orang menyebutnya dengan istilah doyan agama.
Doyan beragama tidak pandang bulu, gampang dideteksi dan ada di setiap agama. Caranya sederhana, cukup dengan pengamatan biasa. Kalau siang hari teriak-teriak membela Allah dan malamnya memosting berita hoax ditambah caption menghasut, itu sudah.
Yang paling fatal begini. Yang mencuitkan berita palsu (hoax) adalah seseorang yang menempati posisi penting dalam urusan agama. Warga media sosial yang berpikir waras kompak merespon. Namun bukannya dengan rendah hati meminta maaf dan mengklarifikasi, ia hanya menghapus cuitannya, tetapi membiarkan ribuan orang share dan menyebar bukan hanya berita palsunya tapi muatan kebencian dan ketidakpercayaan pada pemerintah. Secara sadar ia memperkuat isu-isu SARA!
Dalam konteks politik terkini, kita patut merasa heran, ini sekadar kekeliruan? Apakah hoax sekadar orang orang biasa yang bodoh atau berkaitan dengan sumber (ideologi) dan aktor (influencer)?
Di tengah-tengah kontroversi ini, ketika orang-orang melawan, sejumlah orang ‘bersikap bijak’ dengan mencela mereka yang merespon sang penyebar kebencian dengan logika penyoknya. Mereka menekankan bahwa biar bagaimana pun beliau adalah seorang ulama.
Sebentar, ada yang ganjil. Mereka mencela perlawanan yang sudah sepatutnya demi menjaga marwah sang ulama atau tutup mata dengan kerusakan besar yang sudah dan sedang terjadi?
Sebagai ulama, beliau selayaknya bijak dan belajar dari beberapa kasus sebelumnya. Namun justru berulang lagi. Cuitannya diteruskan ribuan pengikut beragama dan mendalamkan sesat pikir.
Saya tidak suka kondisi ini dan tidak suka dengan bullying berjamaah. Akan tetapi bahwa reaksi publik direduksi sekadar tindakan mencela (ulama), itu sangat takabur! Justru karena ulama, makanya masyarakat mengambil sikap. Sebagian memang kebablasan, dan saya tidak suka. Hanya saja, bagaimana menghentikan sikap semena-mena beliau yang kita tahu dasarnya sangat politis-ideologis ini kalau bukan lewat 'hukuman sosial'?
Cinta super pada ulama sepantasnya tidak melindas daya kritis dan keberanian mengatakan yang benar.
Orang-orang bijak yang mencela orang-orang yang melawan pembusukan akal sehat ini sebaiknya benar-benar bijak. Mereka harus mempertanyakan kembali berdasarkan prinsip apa mereka beroperasi. Jangan sampai kejahatan dibiarkan merajalela semata karena dorongan kesalehan yang sifatnya sekadar mencuci rasa salah. Apalagi semata primordial agama.
A.A. Navis sudah mengajarkan pada kita sebuah pelajaran besar bahwa doyan beragama sangat berbahaya. Apalagi agama yang dipolitisasi, mutlak berbahaya.
Saya pikir, orang-orang bijak tersebut sama naifnya dengan orang-orang beragama egoistis. Di satu sisi, mereka tidak sepakat dengan cuitan yang sangat menghasut tadi. Di sisi lain, mereka seakan mengarahkan perilaku komunitas maya kepada moralisme sempit. Mereka mau melawan hoax tapi mencela mekanisme sosial yang otomatis bekerja 'menghukum' sumber atau aktor atau keduanya?
Sebagai mekanisme sosial, saya pikir sah bila kita memandang respon publik terhadap cuitan tersebut sebagai mekanisme checks and balances, bukan sekadar bullying. Maka bukankah lebih baik bila mengedukasi energi publik yang berdaya punitif (menghukum) supaya lebih elegan dan efektif dalam mengimplementasikan hukuman sosialnya?
Saya pikir, kita harus bersyukur bahwa publik masih memelihara akal sehatnya. Mereka justru tahu menempatkan kehormatan seorang ulama pada tempat yang semestinya. Ketika dalam kesalahan, terbitlah fajar cinta, bukan pembelaan membuta.
Bayangkan bila mayoritas publik mengikuti jalan dan berpikir jalan itulah tujuan. Bukan cuma surau, Republik ini bisa-bisa tersungkur roboh!
Tenun & Batik Rose'S Papua


0 Response to "Robohnya Surau Kami Akibat Doyan Beragama"
Post a Comment